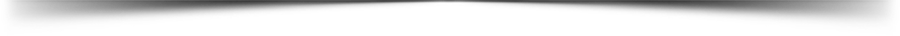Metode Memahami Ajaran Agama
Oleh: ![Anonymous Anonymous]() Anonymous |
Sunday, October 11, 2009
Anonymous |
Sunday, October 11, 2009
Sebagai sesama muslim, dalam rangka tawasau bil-haq wa tawasau bi- shabr, patut kami kemukakan metode memahami ajaran agama yang memadai, santun, bermartabat, dan bertanggung-jawab yang bersumber dari wahyu (Kalam Allah) dan Sunnah Nabi saw.
Secara garis besar dapat dikemukakan dalam dua cara (metode):
Pertama, menyadari akan otoritas hidayah yang hanya datang dari Allah SWT. Siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk-Nya, dan siapa yang tidak dikehendaki-Nya pasti sesat. Semua yang datang dari Allah dan RasulNya adalah konsep abadi yang berlaku secara universal, tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Tidak ada alternatif lain kecuali kita sami’na wa ‘atha’na.
Menurut pandangan pertama ini, kalam Allah adalah berisikan petunjuk untuk dijadikan pedoman hidup dan tidak ada satu kalimatpun yang patut diragukan orisinalitasnya. Bahkan kesempurnaan substansi nya (baca: isi) yang mencakup semua aspek dalam bentuk prinsip-prinsip kehidupan (QS. 5:3) diyakini sebagai sesuatu yang abadi. Bila terdapat masalah-masalah yang musykil itu menjadi tanggung jawab ulama/cendikiawan untuk memberikan jalan keluarnya.
Penyadaran dan keyakinan harus pula ada dalam pemahaman terhadap diri Rasul saw., sebagai uswatun hasanah (QS. 33:21), yang patut dicontoh dalam kehidupan ini. Kepribadian Rasul adalah manifestasi dari isi Al-Qur’an (al-hadis). Tidak ada contoh pribadi unggul yang lebih konkret di muka bumi ini selain yang ada pada diri Rasul saw.
Cara pandang ini adalah bersifat justifikasi untuk mendapatkan keyakinan yang lebih komprehensif. Mempersoalkan hal-hal yang diluar batas kemampuan akal, dapat dianggap pelecehan terhadap kesucian Islam. Islam sebagai agama terakhir, sempurna dan mendapat ridha Allah (QS. 5:3). Siapa yang memilih agama selain Islam, amalnya akan ditolak (QS. 3:85)
Kedua, secara historis, agama Islam adalah sebuah proses panjang sejarah kemanusiaan sesuai sabda Rasul saw., dalam menyempurnakan akhlak. Keberhasilan Rasul saw., merobah masyarakat jahiliyah menjadi bermoral, adalah sebuah khazanah dan tarikh manusiawi yang jauh dari kekudusan. Rasul memang menghadapi banyak keterbatasan dalam usaha menerjemahkan Islam dalam konteks sosial-politik di Madinah, tetapi Ia (Rasul) telah berhasil menerjemahkan cita-cita sosial dan spiritual Islam di Madinah, secara historis, partikular dan kontekstual. Karena itu, umat Islam tidak boleh berhenti berijtihad mencari formula baru dalam menerjemahkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan mereka. Sebab, “Islamnya Rasul di Madinah adalah salah satu kemungkinan menerjemahkan Islam yang universal di muka bumi.” Dengan cara pandang ini, ayat yang berbunyi: “wama yanthiqu ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha”, harus dipahami sebagai pernyataan al-Qur’an dan bukan keseluruhan kata-kata beliau. (QS. An-Najm/53:34)
Cara pandang kedua ini sesungguhnya berimplikasi pada tercemarnya kesucian al-Qur’an itu sendiri. Lebih-lebih penyeragaman sikap kritik literer yang dikembangkan dalam mengkaji karya sastra boleh dan bahkan harus dilakukan atas al-Qur’an agar maknanya dapat ditangkap dengan benar. Dengan demikian, karya-karya masa lalu ulama-ulama terdahulu tidak lagi mendapat tempat yang layak, sebab apalah arti khazanah masa lalu (klasik) jika penalaran telah mampu menjawab tantangan masa kini.
Dari dua cara pandang pemaknaan Islam di atas, tampak terjadi benturan secara diametral yang agak sulit untuk dipertemukan. Padahal agama Islam begitu fleksibel. Bukankah al-Qur’an dapat dibaca ketika kita “bergembira” (syukur) dan dapat pula dibaca ketika kita “dirundung malang”?
Fleksibilitas Islam dapat dilihat dalam ibadah formal, seperti shalat. Nah, kalau dalam ibadah formal masih ada rukhsah (keringanan), mengapa tidak mungkin dalam masalah-masalah yang non formal. Hemat kami, kaidah dalam tradisi Islam: Al-Muhafazhah ‘Ala Al-Qadim Al-Shalih, wa Al-Akhadz bi al-Jadid Al-Ashlah, (mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik) dapat dipakai sebagai acuan paling jitu. Dari kaidah ini, nampak dengan jelas umat Islam dituntut untuk mampu mempertahankan dan mengembangkan yang baik dan membuat “filterisasi” terhadap semua dampak negatif dari berbagai tantangan yang terjadi.
Dipetik dari Buku Dekonstruksi Islam Liberal, Terbitan Pustaka Bayan Tahun 2007
Secara garis besar dapat dikemukakan dalam dua cara (metode):
Pertama, menyadari akan otoritas hidayah yang hanya datang dari Allah SWT. Siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk-Nya, dan siapa yang tidak dikehendaki-Nya pasti sesat. Semua yang datang dari Allah dan RasulNya adalah konsep abadi yang berlaku secara universal, tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Tidak ada alternatif lain kecuali kita sami’na wa ‘atha’na.
Menurut pandangan pertama ini, kalam Allah adalah berisikan petunjuk untuk dijadikan pedoman hidup dan tidak ada satu kalimatpun yang patut diragukan orisinalitasnya. Bahkan kesempurnaan substansi nya (baca: isi) yang mencakup semua aspek dalam bentuk prinsip-prinsip kehidupan (QS. 5:3) diyakini sebagai sesuatu yang abadi. Bila terdapat masalah-masalah yang musykil itu menjadi tanggung jawab ulama/cendikiawan untuk memberikan jalan keluarnya.
Penyadaran dan keyakinan harus pula ada dalam pemahaman terhadap diri Rasul saw., sebagai uswatun hasanah (QS. 33:21), yang patut dicontoh dalam kehidupan ini. Kepribadian Rasul adalah manifestasi dari isi Al-Qur’an (al-hadis). Tidak ada contoh pribadi unggul yang lebih konkret di muka bumi ini selain yang ada pada diri Rasul saw.
Cara pandang ini adalah bersifat justifikasi untuk mendapatkan keyakinan yang lebih komprehensif. Mempersoalkan hal-hal yang diluar batas kemampuan akal, dapat dianggap pelecehan terhadap kesucian Islam. Islam sebagai agama terakhir, sempurna dan mendapat ridha Allah (QS. 5:3). Siapa yang memilih agama selain Islam, amalnya akan ditolak (QS. 3:85)
Kedua, secara historis, agama Islam adalah sebuah proses panjang sejarah kemanusiaan sesuai sabda Rasul saw., dalam menyempurnakan akhlak. Keberhasilan Rasul saw., merobah masyarakat jahiliyah menjadi bermoral, adalah sebuah khazanah dan tarikh manusiawi yang jauh dari kekudusan. Rasul memang menghadapi banyak keterbatasan dalam usaha menerjemahkan Islam dalam konteks sosial-politik di Madinah, tetapi Ia (Rasul) telah berhasil menerjemahkan cita-cita sosial dan spiritual Islam di Madinah, secara historis, partikular dan kontekstual. Karena itu, umat Islam tidak boleh berhenti berijtihad mencari formula baru dalam menerjemahkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan mereka. Sebab, “Islamnya Rasul di Madinah adalah salah satu kemungkinan menerjemahkan Islam yang universal di muka bumi.” Dengan cara pandang ini, ayat yang berbunyi: “wama yanthiqu ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha”, harus dipahami sebagai pernyataan al-Qur’an dan bukan keseluruhan kata-kata beliau. (QS. An-Najm/53:34)
Cara pandang kedua ini sesungguhnya berimplikasi pada tercemarnya kesucian al-Qur’an itu sendiri. Lebih-lebih penyeragaman sikap kritik literer yang dikembangkan dalam mengkaji karya sastra boleh dan bahkan harus dilakukan atas al-Qur’an agar maknanya dapat ditangkap dengan benar. Dengan demikian, karya-karya masa lalu ulama-ulama terdahulu tidak lagi mendapat tempat yang layak, sebab apalah arti khazanah masa lalu (klasik) jika penalaran telah mampu menjawab tantangan masa kini.
Dari dua cara pandang pemaknaan Islam di atas, tampak terjadi benturan secara diametral yang agak sulit untuk dipertemukan. Padahal agama Islam begitu fleksibel. Bukankah al-Qur’an dapat dibaca ketika kita “bergembira” (syukur) dan dapat pula dibaca ketika kita “dirundung malang”?
Fleksibilitas Islam dapat dilihat dalam ibadah formal, seperti shalat. Nah, kalau dalam ibadah formal masih ada rukhsah (keringanan), mengapa tidak mungkin dalam masalah-masalah yang non formal. Hemat kami, kaidah dalam tradisi Islam: Al-Muhafazhah ‘Ala Al-Qadim Al-Shalih, wa Al-Akhadz bi al-Jadid Al-Ashlah, (mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik) dapat dipakai sebagai acuan paling jitu. Dari kaidah ini, nampak dengan jelas umat Islam dituntut untuk mampu mempertahankan dan mengembangkan yang baik dan membuat “filterisasi” terhadap semua dampak negatif dari berbagai tantangan yang terjadi.
Dipetik dari Buku Dekonstruksi Islam Liberal, Terbitan Pustaka Bayan Tahun 2007